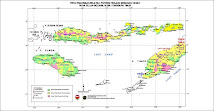Menyingkap Misteri, Membangun Empati
KO M PA S / P R I YO M B O D O / Kompas Images
BUDIAWAN
Sejarawan Ong Hok Ham (almarhum) pernah melontarkan skeptisismenya terhadap upaya alternatif menemukan dalang Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Kesangsiannya ini merupakan respons atas silang pendapat mengenai dalang di balik penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965.
Silang pendapat itu muncul tidak lama setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998. Tentu bukan maksud Ong untuk membela versi resmi rezim Orba yang secara gampangan menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang G30S. Kesangsian Ong mencerminkan posisinya sebagai sejarawan profesional, yang berpegang pada prinsip bahwa sejarah tidak mungkin ditulis tanpa bukti yang memadai.
Menyangkut G30S, bukti-bukti yang tersedia sangat jauh dari mencukupi karena banyak pelaku yang terlibat dalam gerakan itu, yang notabene bisa menjadi saksi kunci, telah dibunuh oleh Angkatan Darat, tidak lama setelah peristiwa itu terjadi.
Buku John Roosa, dosen sejarah di University of British Columbia, Kanada, yang merupakan hasil penelitian selama lima tahun ini, seperti hendak menjawab skeptisisme dan pesimisme semacam itu. Bukan dengan menyodorkan sebuah jawaban pasti atas pertanyaan siapa dalang G30S, tetapi dengan menunjukkan bahwa pertanyaan itu memang tidak akan pernah terjawab karena asumsinya keliru secara faktual.
Pertanyaan siapa dalang G30S mengasumsikan bahwa G30S merupakan sebuah gerakan yang terorganisasi secara rapi, dengan struktur hierarki wewenang dan pembagian tugas yang jelas serta ada pucuk pimpinan tunggal.
Menurut Roosa, asumsi ini keliru karena G30S kenyataannya jauh dari gambaran seperti itu. Sebagai sebuah operasi militer rahasia yang melibatkan beberapa pemimpin teras PKI, G30S merupakan sebuah gerakan yang kompleks, ruwet, dan tak jelas struktur organisasinya ataupun koordinasi pelaksanaannya. Tak ada garis komando yang jelas siapa memerintahkan siapa untuk tugas apa.
Sjam Kamaruzaman adalah Ketua Biro Chusus PKI yang menjadi perantara Ketua CC-PKI DN Aidit dan sekelompok ”perwira progresif” (Letkol Untung Sjamsuri dan kawan-kawan) yang tergabung dalam G30S. Tetapi, tidak jelas apakah Aidit sebagai pengendali G30S ataukah sekadar diseret ke dalamnya karena adanya kesamaan kepentingan dengan para ”perwira progresif” itu, yaitu memereteli kekuasaan sekelompok perwira kanan (AH Nasution dan kawan-kawan) melalui tangan Sukarno.
Ide menculik Nasution dan kawan-kawan serta menghadapkan mereka kepada Sukarno diyakini sebagai cara yang efisien dan terhormat untuk melumpuhkan pengaruh para perwira kanan dalam perpolitikan nasional. Skenario itu gagal total karena buruknya koordinasi di lapangan dan rendahnya kompetensi para prajurit pelaksana operasi itu. Hal ini menyebabkan Sukarno tidak mendukung, tetapi juga tidak mengecam G30S.
Dua hari setelah kejadian itu Sukarno memerintahkan Untung dan kawan-kawan untuk membubarkan G30S. Untung pun mematuhinya. Tetapi, Aidit, yang sudah lari menyembunyikan diri di Jawa Tengah, ingin gerakan itu diteruskan sambil berharap ada dukungan Sukarno. Anehnya, ia sama sekali tidak menggunakan organ-organ PKI untuk melanjutkan gerakan. Ia hanya pasif menunggu dukungan Sukarno, tidak tahu bahwa Sukarno telah memerintahkan pembubaran G30S.
Selanjutnya adalah serangan balik Soeharto, yang sudah mengetahui sebelumnya tentang akan adanya aksi G30S itu berkat pemberitahuan Latief. Serangan balik ini hanya awal dari pengejaran, pembantaian, dan penahanan massal terhadap siapa saja yang dianggap punya kaitan dengan PKI atau ormas-ormasnya. Meskipun demikian, tidak masuk akal dan juga tidak ada bukti yang memadai untuk mengatakan Soeharto dalang G30S.
Tampak bahwa alih-alih berusaha menemukan dalang, Roosa berupaya mencari tahu ”apa yang paling mungkin terjadi dengan G30S”. Meskipun tidak berakhir dengan kepastian karena penulisan sejarah yang penuh kepastian justru mengundang kecurigaan, buku ini sekurang-kurangnya telah menyibak sebagian misteri di seputar G30S.
Rekonstruksi
Meskipun buku ini ditulis dengan tujuan merekonstruksi masa lalu, struktur gagasan buku ini berbeda dari buku sejarah pada umumnya. Alih-alih ditulis dengan alur awal-klimaks-akhir, buku ini disusun berdasarkan potongan-potongan data, tak lain untuk mendapatkan gambaran fakta yang selengkap mungkin.
Dengan itu justru terlihat keganjilan hubungan antarfakta sehingga tujuan memahami ”apa yang paling mungkin terjadi” pun relatif bisa tercapai. Metode ini mirip dengan cara kerja detektif yang berangkat dari ketidaktahuan, bergulat dengan serpihan-serpihan data, mengutak-atik ada/tidaknya hubungan antarfakta, dan berakhir dengan dugaan-dugaan kuat bahwa kepastian mustahil didapat.
Potongan data yang menjadi titik tolak penyelidikan Roosa adalah dokumen Supardjo, yang kemudian ia kembangkan dengan mempelajari potongan-potongan data lain, yakni hasil wawancaranya dengan seorang mantan kader tinggi PKI, dokumen-dokumen internal PKI, beberapa memoar eks tapol yang baru diterbitkan, dan dokumen-dokumen rahasia Pemerintah AS yang sudah dideklasifikasikan. Setiap sumber dianalisis dan selanjutnya Roosa berupaya membangun suatu narasi yang berjalan secara kronologis dan bermaksud memecahkan banyak keganjilan yang telah ia uraikan sebelumnya.
Cara kerja ini berbeda dari kebanyakan pengkaji G30S lainnya, yang dengan sepotong data langsung membangun kesimpulan sehingga penyelidikan selanjutnya tak lebih dari upaya pembuktian kesimpulan itu. Karena beragam peneliti menggenggam beragam potongan data, hasilnya adalah munculnya beragam versi, misalnya (a) Sukarno dalang G30S (Fic, 2004), (b) Soeharto dalang G30S (Wertheim, 1970), (c) G30S sebagai konflik internal Angkatan Darat (Anderson and McVey, 1971), (d) CIA dalang G30S (Scott, 1985), (e) MI-6 dalang G30S (Poulgrain, 2000), dan (f) PKI dalang G30S (buku putih Orde Baru).
Selain tak akan pernah memuaskan secara akademis, munculnya beragam versi itu hanya menimbulkan silang pendapat yang tak akan berkesudahan, yang berakibat pada pengabaian dan pelupaan atas tragedi kemanusiaan yang lebih besar, yakni pembantaian dan pemenjaraan massal terhadap ratusan ribu bahkan mungkin jutaan anggota dan simpatisan PKI atau yang sekadar di-PKI-kan, yang terjadi sejak tiga minggu setelah 30 September 1965 hingga pertengahan 1966.
Dengan kata lain, buku ini mengajukan argumentasi utama sebagaimana tertuang dalam judulnya, yaitu menempatkan G30S sebagai ”Dalih Pembunuhan Massal”, yang bersamanya Soeharto dengan dukungan para perwira kanan AD melakukan kudeta terhadap Sukarno. G30S dan kudeta Soeharto dengan demikian adalah dua peristiwa yang terpisah, yang terjadi secara berurutan, tetapi bukan dalam hubungan sebab-akibat.
Dengan argumentasi itu, Roosa ingin mengatakan bahwa G30S mempunyai makna penting karena Soeharto dan para perwira kanan AD yang telah lama menunggu-nunggu kesempatan untuk menghancurkan PKI sebagai jalan mengambil alih kekuasaan Sukarno menganggapnya demikian.
Indikator utamanya adalah begitu cepat dan masifnya propaganda penghancuran PKI mulai dikobarkan, hanya tiga hari setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira AD terjadi. Dari mana AD tahu dalam tempo sesingkat itu bahwa kejadian dini hari 1 Oktober 1965 didalangi oleh PKI?
Pertanyaan itu tidak relevan karena bukti bukan dicari, tetapi dikarang-karang. Salah satu ”bukti yang dikarang-karang” yang kemudian mendorong histeria massa anti-PKI adalah ”dongeng Lubang Buaya”, yang kemudian diabadikan dalam Monumen Pancasila Sakti dan disebarluaskan melalui berbagai cara, termasuk film garapan Arifin C Noor yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI. Sedemikian intensifnya penyebarluasan dan pewarisan ”dongeng Lubang Buaya” ini sehingga terbentuklah sebuah memori nasional yang sama sekali tidak mengacu pada apa yang sesungguhnya terjadi.
Apakah dengan demikian Roosa ingin membersihkan nama PKI? Apakah ia bermaksud membela PKI?
Profesional
John Roosa adalah seorang sejarawan profesional. Selain bekerja dengan etika akademis, ia juga menulis sejarah dengan spirit human concern. Seperti tertulis dalam kata pengantar buku ini tampak bahwa sikap Roosa tidak membela aksi-aksi PKI sebelum 1965, tetapi sama sekali juga tidak membenarkan kekerasan massal yang diarahkan kepada PKI setelah G30S.
Roosa ingin menghancurkan cara berpikir dikotomistik bahwa kalau tidak anti-PKI pasti pro-PKI dan sebaliknya. Selama cara berpikir seperti ini terus dipegang, niscaya kita akan terus gagal melihat peristiwa 1965-1966 sebagai bencana kemanusiaan. Cara pandang kita akan terus didikte oleh prasangka ideologis abstrak dan kalkulasi politik sempit.
Roosa menambahkan, sudah saatnya pula untuk berhenti berpikir mengikuti stereotip-stereotip basi. Sepanjang kekuasaan Soeharto, PKI digambarkan sebagai momok jahat sehingga tidak mungkin memahami bagaimana partai itu pernah menjadi demikian populer, dengan jutaan anggota dan simpatisan. Bagaimana mungkin sebegitu banyak orang Indonesia dihujat sebagai iblis? Buku ini ditulis berdasarkan anggapan bahwa anggota PKI sebenarnya manusia, bukan setan, dan memiliki karakter moral yang tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang-orang lain di Indonesia (halaman xix).
Pesan etis tersebut sama dengan pendapat seorang sarjana literary theories Rusia, Tzvetan Todorov, yang menyatakan bahwa begitu kita menghujat masa lalu, kita tidak akan pernah belajar apa pun dari masa lalu itu. Hal yang sebaliknya saya kira juga berlaku: begitu kita terus-menerus mengglorifikasi masa lalu, kita juga tidak akan pernah belajar apa pun dari masa lalu itu.
Begitu dekatnya hubungan antara sejarah dan etika sehingga sejarah masih berhak mengklaim sebagai bagian dari humaniora, bukan instrumen pembenar kekuasaan suatu kelompok atau sikap politik suatu golongan.
Budiawan Dosen Program Magister Kajian Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta




.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)